DiksiNasi, CIAMIS – Fenomena Warga Segel Kantor Desa dan aksi demonstrasi yang marak belakangan ini tidak bisa hanya dibaca sebagai ledakan emosi warga terhadap kepala desa.
Lebih dari itu, gejala ini mencerminkan krisis multidimensi yang menggerogoti fondasi pemerintahan desa: dari lemahnya transparansi anggaran, kepemimpinan yang defisit etika, hingga pola patronase politik yang menjalar sampai ke akar rumput.
Politik Uang dan Nafsu Kekuasaan di Tingkat Desa
Pilihan menjadi kepala desa kini bukan lagi sekadar pengabdian sosial, tetapi telah menjelma sebagai pintu masuk ke dalam sirkuit kekuasaan lokal.
Dalam banyak kasus, pencalonan kepala desa dimulai dengan transaksi yang membebani kandidat secara finansial.
Biaya kampanye yang besar, politik uang, hingga komitmen “balas budi” pasca terpilih, menjadi beban yang membentuk kultur oligarkis mini di dalam desa.
Ketika kursi sudah diraih, realitas tak kalah getir menanti.
Banyak kepala desa tidak memiliki kesiapan mental maupun spiritual untuk mengelola amanah.
Tekanan dari para pendukung, kebutuhan untuk “mengembalikan modal”, serta godaan untuk membangun dinasti politik membuat posisi ini rawan disalahgunakan.
Dana Desa: Anugerah yang Menjadi Jerat
Sejak menggelontornya Dana Desa lewat skema pembangunan partisipatif, desa-desa di Indonesia mengelola triliunan rupiah anggaran publik.
Namun, praktik pengelolaan dana ini masih menyisakan persoalan akut: akuntabilitas yang minim, akses informasi yang tertutup, serta literasi anggaran masyarakat yang rendah.
UU Nomor 6 Tahun 2014 memang memberikan otonomi pada desa.
Tapi tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif warga, otonomi ini rawan tersamarkan menjadi absolutisme lokal.
Di sinilah letak akar krisis: warga tidak tahu ke mana aliran dana publik mengalir, dan ketika suara mereka tak ada yang mendengar, jalan demonstrasi hingga penyegelan kantor desa menjadi pilihan ekstrem.



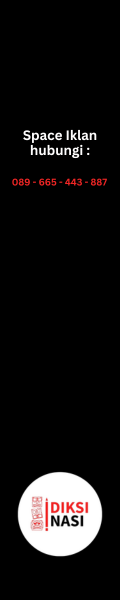

















Komentar