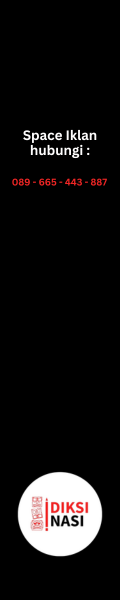DiksiNasi, Ciamis – Kosongnya kursi Wakil Bupati Ciamis periode 2025–2030 menjadi ironi dalam pesta demokrasi lokal.
Dalam Pemilihan Umum Bupati Ciamis yang digelar 27 November 2024 lalu, rakyat hanya disodori satu pasangan calon: H. Herdiat Sunarya dan almarhum H. Yana D Putra.
Tanpa ada lawan, tanpa ada pilihan.
Demokrasi lokal pun berjalan seperti rutinitas administratif belaka.
Bukan kontestasi ide dan gagasan, melainkan hanya formalitas elektoral.
DPRD Ciamis secara resmi menetapkan pasangan Herdiat-Yana sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Rapat Paripurna di Aula Tumenggung Wiradikusumah pada 14 Januari 2025.
Namun, hanya menetapkan Herdiat.
Pada 20 Februari 2025, ia diambil sumpahnya di Istana Negara Jakarta bersama 480 kepala daerah lainnya, dalam pelantikan serentak pertama dalam sejarah Republik.
Sementara sang wakil, H. Yana D Putra, telah wafat sebelum pemungutan suara.
Kursinya kini kosong.
Demokrasi Tanpa Pilihan
Kosongnya kursi wakil bupati ini bukan sekadar kecelakaan politik, melainkan cerminan dari mandeknya regenerasi dan pembusukan sistem.
Padahal, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024 membuka peluang besar.
Dengan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024 yang dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, partai politik tanpa kursi di DPRD pun dapat mengusung pasangan calon kepala daerah, asalkan meraih suara sah minimal 7,5% dari jumlah DPT.
Di Ciamis, dengan DPT sebanyak 965.599 pemilih, setidaknya ada delapan partai politik yang memenuhi ambang batas untuk mengusung calon sendiri tanpa perlu berkoalisi: PDI-P (16,02%), PAN (13,54%), PKS (12,50%), Gerindra (11,11%), PKB (9,46%), Golkar (9,29%), Demokrat (8,58%), dan PPP (7,93%).
Lalu mengapa tidak ada satupun partai yang benar-benar menggunakan peluang itu untuk menampilkan alternatif pemimpin?
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan ini tidak boleh menguap begitu saja.
Fenomena ini bukan hanya soal satu pasangan calon, melainkan soal minimnya tanggung jawab kolektif dalam merawat kualitas demokrasi lokal.
Partai politik, yang semestinya menjadi pabrik gagasan dan kaderisasi pemimpin, justru menjelma menjadi gerbong pragmatis.
Mereka memilih aman, ikut mengusung petahana, atau tidak ikut sama sekali.
Di saat peluang konstitusional terbuka lebar, mereka justru menutup pintu bagi munculnya calon alternatif.
Ini bukan hanya soal malas bertarung, tapi juga soal mentalitas elite yang enggan mengambil risiko demi rakyat.
Kader partai, yang berada di level akar rumput, pun tampak pasrah.
Tidak ada dorongan dari bawah untuk memunculkan calon baru.
Ini adalah kegagalan kaderisasi yang sistemik.
Akademisi dan aktivis, yang selama ini digadang-gadang sebagai penjaga moral demokrasi, seolah memilih diam.
Kampus yang mestinya menjadi rumah diskusi dan dialektika politik justru sunyi dari suara kritis.
Aktivis lebih sibuk dengan isu nasional ketimbang mengawal demokrasi di halaman rumah sendiri.
Lembaga negara seperti Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu, pun patut dievaluasi.
Sejauh mana mereka menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik?
Apakah selama ini mereka hanya menjadi fasilitator teknis pemilu, tanpa ikut menciptakan ekosistem politik yang sehat dan partisipatif?
Dalam demokrasi, ketidakpedulian adalah bentuk paling halus dari pengkhianatan.