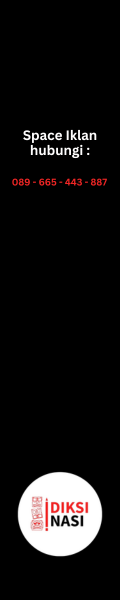Pasalnya, berdasarkan catatan Tren Vonis ICW sepanjang tahun 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan.
Pertanyaannya, bagaimana bisa pemerintah dan DPR berpikir bahwa di tengah meningkatnya kasus korupsi dan rendahnya hukuman bagi koruptor, justru dijawab dengan menurunkan ancaman hukum penjara bagi pelaku?
Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasyarakatan yang memberikan kemudian bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti, serta tidak harus menjadi justice collaborator.
Ketiga, tidak memasukkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini tentu semakin meruntuhkan semangat pengembalian aset hasil kejahatan.
Catatan ICW dalam tren vonis 2021, dari total kerugian negara sebesar Rp 62,9 triliun, uang pengganti hanya mencapai Rp 1,4 triliun.
Pada saat yang sama, sejumlah regulasi penting seperti rancangan UU Perampasan Aset justru tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.
Baca Juga : 31 Mahasiswa Pendemo Tolak KUHP Ditangkap di Bandung, Ratusan Organisasi Kecam Tindakan Represif Polisi
Baca Juga : Bolehkah PNS, Honorer, hingga Polisi Nyambi Jadi Wartawan?
Keempat, berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Sebab, dalam penjelasan pasal 603 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara.
Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagaimana diketahui, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap kali memakan waktu lama sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum.
Pengaturan dalam KUHP tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK saat menghitung kerugian negara.
Akan tetapi, juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan memungkinkan penegak hukum untuk dapat membuktikan sendiri di luar temuan lembaga negara tersebut.
Berdasarkan argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi pasal tipikor dalam KUHP menjadi ‘kado manis’ dan karpet merah bagi koruptor untuk kesekian kalinya. Hal ini menambah daftar panjang rentetan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi.
Pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang mengatakan, bahwa jika masyarakat tidak puas dengan pasal dalam KUHP dapat mengajukan judicial review ke MK.
Baca Juga : Ciamis Masuk Tiga Besar Kabupaten/Kota Penghasil Sampah Terbanyak di Jawa Barat (2021)
Baca Juga : LPSE Hambat Masyarakat Ketahui Informasi Publik, Ada Apa Sebenarnya ?
Namun hal ini pun rasanya percuma dilakukan sebab, bukan tidak mungkin keputusan hakim MK nantinya tidak akan objektif karena dibayang-bayangi rasa takut akan bernasib sama dengan Hakim Aswanto yang dicopot dengan alasan kerap menganulir produk DPR.
Di luar itu, sikap komisioner KPK juga patut mendapat sorotan, Sebab, atas masalah ini, kelima pimpinan lembaga antikorupsi bahkan tidak menunjukkan sikap sama sekali. Hal ini berbanding terbalik dengan komisioner pada periode sebelumnya yang menyiapkan catatan kritis ketika akan diundang oleh Presiden untuk membicarakan masalah pasal tipikor dalam RKUHP.